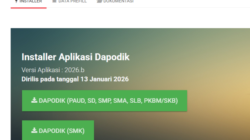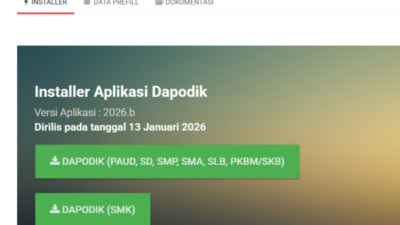Sebagai guru, membaca hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 memunculkan perasaan yang campur aduk. Ada rasa gelisah, ada rasa prihatin, juga ada rasa lelah. Ini karena sekali lagi guru berada di posisi yang mudah disalahkan. Ketika media ramai menggunakan kata “jeblok”, dan sorotan diarahkan ke daerah tertentu seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), kami di ruang kelas tahu bahwa persoalan ini tidak sesederhana itu.
Guru hidup di tengah proses belajar yang nyata, bukan di atas kertas kebijakan. Karena itu, hasil TKA perlu kita baca dengan kepala dingin dan hati yang adil.
Secara nasional, capaian TKA menunjukkan angka yang tidak tinggi pada mata pelajaran inti. Matematika ada di kisaran 30-an, sementara Bahasa Inggris di kisaran 20-an. Angka ini muncul hampir merata di berbagai provinsi. Ini berarti realitasnya bukan gagal di satu sekolah, satu daerah, atau di satu kelompok guru, tetapi ini adalah masalah sistem pembelajaran secara nasional.
Di NTT, capaian TKA memang ada di bawah rata-rata nasional. Namun selisihnya tidak besar dan mengikuti pola nasional yang sama. Dari sudut pandang (saya) sebagai guru, hal ini justru menegaskan bahwa di NTT ini bukan seuatu yang tidak wajar. NTT memperlihatkan lebih jelas dampak dari ketimpangan yang sudah lama ada: keterbatasan sarana, akses belajar yang tidak merata, dan ekosistem literasi yang belum kuat sejak pendidikan dasar pun di lingkungan keluarga.
Sebagai guru di sekolah, kita sudah tahu dahulu bahwa TKA tidak hanya mengukur hafalan. Soal-soalnya butuh penalaran level dewa, pemahaman konteks, dan kemampuan membaca yang mendalam. Namun kami juga tahu, praktik pembelajaran sehari-hari masih sering terjebak pada tuntutan menyelesaikan materi, mengejar administrasi, dan menyiapkan siswa untuk jenis evaluasi lama yang menekankan jawaban benar, bukan proses berpikir.
Di sinilah ketegangan itu terjadi. Guru diharapkan / dituntut membentuk cara berpikir tingkat tinggi, tetapi bekerja dalam sistem yang belum sepenuhnya memberi ruang dan dukungan ke arah itu. Ketika alat ukurnya berubah lebih cepat daripada praktik belajar di kelas, maka yang muncul bukan peningkatan kualitas, melainkan KEGAGAPAN BERJAMAAH!.
Sebagai guru, kami tidak tolak evaluasi. Bahkan ada yang bilang “bagaimana kalau soal-soal TKA itu diujikan ke guru-guru dulu” oke fine….saya siap. Tapi apa itu solusi? atau hanya sentilan untuk mengkambinghitamkan guru?
Data hasil TKA ini tentu sangat penting sebagai CERMIN. Cermin yang baik tidak digunakan untuk menghakimi, melainkan untuk berkaca (orang Kupang bilang “loti”) memperbaiki diri . Jika hasil TKA dibaca tanpa konteks, guru mudah dijadikan sasaran empuk, seolah-olah semua kegagalan berakar pada ruang kelas semata.
Padahal, ruang kelas tidak berdiri sendiri. Cara guru mengajar sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka dididik, dilatih, dan didampingi. Pendidikan calon guru, kebijakan pelatihan, beban administrasi, hingga budaya penilaian di sekolah membentuk praktik mengajar sehari-hari. Menuntut guru berubah tanpa mengubah sistem yang mengungkungnya adalah tuntutan yang tidak adil.
Di daerah seperti NTT, tantangan ini berlapis. Keterbatasan buku, akses teknologi yang tidak merata, dan kondisi sosial ekonomi peserta didik sangat memengaruhi proses belajar. Tetapi pengamatan saya, ada juga daerah dengan fasilitas lebih baik pun dihadapkan pada persoalan serupa dalam hal penalaran dan literasi. Ini pertanda bahwa persoalannya tidak semata tentang infrastruktur, tetapi paradigma pembelajaran yang berlaku secara luas.
Label “daerah tertinggal” sering kali justru melukai semangat belajar. Anak-anak di NTT memiliki potensi yang sama dengan anak-anak di mana pun. Yang berbeda adalah kesempatan dan dukungan yang mereka terima. Guru melihat langsung bagaimana stigma dapat memengaruhi kepercayaan diri siswa, padahal pendidikan seharusnya menumbuhkan harapan.
Bagi guru, TKA seharusnya menjadi peringatan dini. Ia mengingatkan bahwa selama ini kita mungkin terlalu nyaman dengan kelulusan administratif dan nilai rapor, tanpa memastikan pemahaman yang sungguh-sungguh. Banyak siswa naik kelas, tetapi belum benar-benar kuasai cara berpikir yang adalah dasar pembelajaran lanjutan.
Namun peringatan ini hanya akan bermakna jika ditindaklanjuti dengan kebijakan yang berpihak pada proses belajar. Guru membutuhkan pendampingan pedagogis, waktu untuk refleksi, dan ruang untuk mengubah praktik mengajar tanpa ketakutan disalahkan. Reformasi pendidikan tidak bisa dibangun di atas rasa curiga terhadap guru.
Sebagai guru, kami berharap hasil TKA dibaca sebagai undangan untuk bekerja bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kampus pendidikan guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu duduk dalam satu kerangka perbaikan. Data harus menjadi dasar pengambilan kebijakan yang kontekstual, terutama bagi daerah yang selama ini menanggung beban ketimpangan.
NTT bukan daerah gagal. Dari ruang kelas, kami melihat anak-anak yang ingin belajar dan guru-guru yang terus berusaha di tengah keterbatasan. Jika perbaikan sistem dilakukan dengan serius di daerah seperti NTT, maka hasilnya justru bisa menjadi model pembelajaran nasional yang lebih adil dan manusiawi.
TKA 2025 telah membuka tabir yang selama ini tertutup. Sebagai guru, kami tidak meminta untuk dibela, tetapi untuk dipahami. Pendidikan tidak akan maju dengan saling menyalahkan. Ia hanya bisa bertumbuh jika kita berani melihat persoalan secara utuh dan memperbaikinya bersama. Salam Manis dari Sini untukmu yang di SANA!